
JAKARTA— Aktivitas mudik dan perayaan Idul Fitri sudah berlalu. Kegiatan kolosal yang menjadi tradisi periodik tiap tahunnya memiliki impact fitrah yang cukup berarti dalam menata ulang tentang kepribadian kita dalam relasinya dengan Tuhan dan sesama.
Bagi kebanyakan orang, kegiatan mudik bukan sekadar mobilitas orang dari kota ke desa atau transformasi pergerakan yang berada di perantauan kembali ke kampung halaman, melainkan lebih dari itu, mudik adalah momentum jeda aktivitas yang membangun kesadaran tentang asal-usul dengan menjauhi hiruk-pikuk kegiatan rutinan, termasuk pekerjaan.
Begitu pula dengan Idul Fitri. Kemenangan yang dirakayakan dalam setiap jengkal kegiatan berupa gema takbir dan ucapan minal aidin wal faizin di emperan masjid, mushala, rumah, jalanan, dan media sosial, riang anak-anak yang memainkan petasan, orang-orang yang hilir-mudik mengantarkan ‘sadaqahan’ hingga takbir keliling yang memoles panorama pesona satu hari satu malam.
Hal yang paling primordial dari ritus perayaan tahunan itu adalah kondisi seseorang yang mendapatkan kondisi ‘kembali suci’ dengan melepas kesalahan dengan ‘maaf-maafan’, membangun modalitas transedentif yang lebih segar dalam melaksanakan amalan syar’iyah, sehingga kesiapan fisik dan mentalitas beragama seorang hamba terbangun ulang ke depan.
Secara esensial, mudik, Idul Fitri, dan ‘syawalan’ menjadi hal yang identik, saling jalin berkelindan sebagai momentum sakral dalam lintasan tahunan umat Islam (Andi, 2022). Nuansa itu identik dengan kefitrian; mudik adalah fitri dengan kembali ke asal dan Idul Fitri adalah kefitrian jiwa sebagai hakikat ontis dari manusia. Ini yang kemudian dikenal dengan tren spritualitas tahunan di mana terdapat ritus berkala sebagai momentum menaja ulang keberagamaan kita.
Tidak ayal jika bulan Syawal (syala, syawwal, Arab) secara sentatik bermakna naik, meninggi, atau dibesarkan, karena jatuhnya sebagai bulan kesepuluh dalam kalender Hijriyah berada pasca-Ramadan di mana kefitrian seseorang terbentuk dan spirit keagamaan terbangun. Inilah sisi keistimewaan dari Syawal yang meskipun secara dogma religiusitas terlupakan dalam lintasan Rajab, Syaban, dan Ramadan.
Terdapat beberapa keistimewaan Syawal. Seperti Idul Fitri yang jatuh pada tanggal satu bulan Syawal, ajaran puasa ‘syawalan’ yang sebanding dengan puasa satu tahun (HR Bukhori), dan anjuran silaturrahim (halal bihalal, QS An Nisaa: 36).
Di samping itu, kefitiran yang dimanifestasikan dalam spirit keagamaan juga memiliki rajutan historisnya sendiri di bulan Syawal yaitu bagaimana Rasulullah SAW dan para Sahabat terdahulu menghias corak Syawal dengan nunsa keberagamaan.
Pada Syawal banyak terjadi perang, seperti Perang Bani Qainuqa pada tahun kedua Hijriyah, Perang Uhud pada 17 Syawal tahun ketiga Hijriyah, Perang Khandaq pada 18 Syawal tahun kelima Hijriyah, perang Hunain pada 6 Syawal tahun kedelapan Hijriyah dan pada tahun keempat belas Hijriyah terjadi penaklukan Madain, ibu kota Imperium Persia.
Kita mengetahui bahwa perang dan ekspansi dakwah keislaman adalah salah satu bagian jalan proses Islamisasi dan ekspansi kekuasaan sebagai jalan terkahir di mana legal survive berlaku di sana.
Meskipun terdapat musibah di dalamnya, seperti kekalahan umat Islam pada perang Uhud (QS Ali Imran ayat 121), spirit dakwah mewujud perjuangan Islamisasi kental terasa di bulan Syawal dengan kandungan pelajaran bermakna di baliknya.
Pada Syawal juga, pada 27 Syawal di Tahun kesepuluh kenabian, Rasulullah SAW melakukan dakwah ke kota Thaif setelah mendapat penolakan dan tidak menemukan ruang dakwah di kota Makkah. Meski kondisi dakwah yang tidak jauh berbeda di Thaif, ada usaha hijrah yang dilakukan oleh Nabi di sini ketika terjadi kevakuman dan stagnasi dakwah keislaman.
Tidak kalah unik, Syawal juga identik dengan ‘bulan nikah’. Memang tidak dimungkiri ibadah penyempurnaan iman itu memiliki riwayat tersendiri pada Syawal.
Rasulullah SAW melakukan dua kali pernikahan di bulan Syawal, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah menikahi Sayyidah Aisyah Binti Abu Bakar dan pada tahun keempat Hijriyah Nabi menikahi Ummu Salamah. Seperti riwayat hadits dari Aisyah RA berikut ini:
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahiku pada Syawwal dan berkumpul denganku pada bulan Syawwal, maka siapa di antara istri-istri beliau yang lebih beruntung dariku?” ( HR Muslim no 2551, At-Tirmidzi no 1013, An Nasai no 3184, Ahmad no 23137 )
Rajutan Histroris keislaman di bulan Syawal menjadi bukti adanya spirit keagamaan yang berhasil direfleksikan dari kondisi fitrah di Bulan Ramadan. Secara implikatif, Idul Fitri dan tradisi mudik pada tiap tahunnya pada tataran tertentu memiliki imperatif moral yang berkelanjutan.
Artinya, semangat ubudiyah dan kemanusiaan, seperti ‘khataman’ dan ‘shadaqhan’, yang secara ‘fastabiqul khairat’ dilakukan pada Ramadan tidak berlalu bersamaan dengan kemenangan yang diraih.
Berlalunya momentum Idul Fitri dan kembalinya rutinitas sosial pasca mudik, bukan berarti spirit keagamaan yang dibangun dari impact kefitrian juga usang.
Ada entitas sprirtual yang harus kita rawat dan kita tingkatkan kualitasnya. Sehingga ritus spritualitas tahunan Idul Fitri dan tradisi mudik secara substansial bisa membentuk kepribadian Muslim yang hakiki. Mari terus merawat kefitrahan, wallahu a’lam. (A Fahrur Rozi, ed: Nashih).

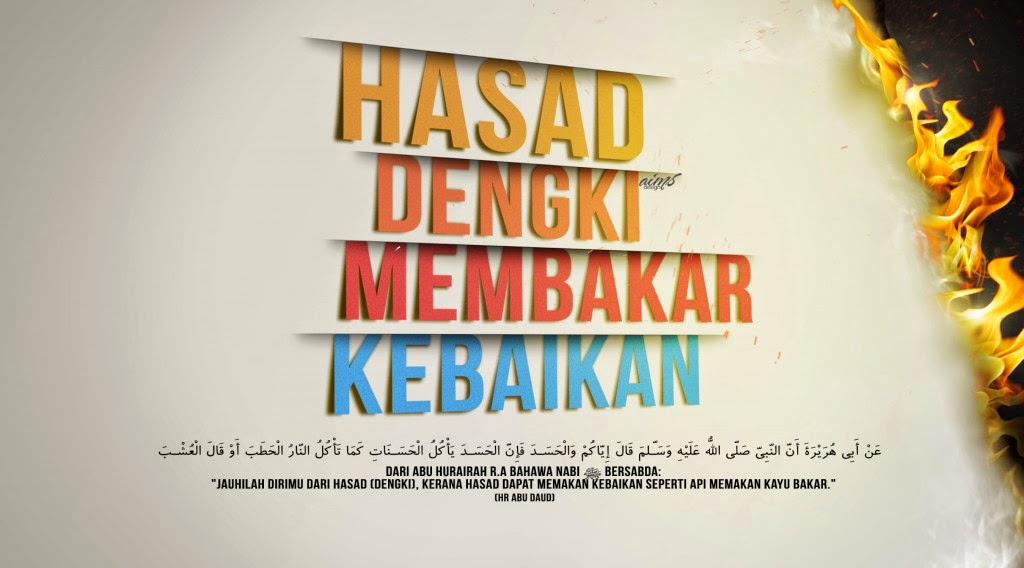


Leave a Reply